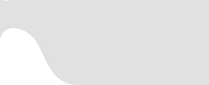
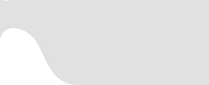 |
Sinergi Agama Hindu dan Budaya Bali sumber: Parisada Hindu Dharma Indonesia
Quote:
Pada tahun 2006 yang lalu Bali dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata yang eksotik dunia, dan tentunya dengan predikat tersebut diharapkan kunjungan wisatawan akan semakin banyak mengunjungi Bali. Bali sebagai salah satu destinasi wisatawan dunia sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda di Inonesia. Dengan maskapai KLM milik pemerintah Belanda, secara periodik wisatawan Eropa mengunjungi Bali dan sejak saat itu Agama Hindu dan budaya Bali sangat menarik perhatian mereka. Banyak karya seni dan kerajinan masyarakat Bali yang dibawa ke Eropa, dan menjadikan Bali semakin dikenal. Perhatian dunia kepada Bali semakin besar, ketika tim kesenian Bali yang mementaskan tari-tarian klasik seperti Barong melanglang Eropa, Amerika, dan Australia yang menjadikan pulau dewata ini berbenah diri, menghadapi dan menerima kunjungan wisatawan ke Bali. Wisatawan asing tertarik dengan Bali utamanya adalah karena faktor budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu. Agama Hindu memberi nafas hidup dan pencerahan terhadap budaya Bali dan di Bali antara Agama Hindu dan budaya Bali bersinergi sedemikian rupa, jalin-menjalin bagaikan kain tenun ikat, saling memperkuat dan saling memberikan sumbangan yang tidak dapat dipisahkan. Sinergi Agama Hindu dengan budaya Bali ini, bagaikan sekeping mata uang logam yang bila dipisahkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, mata uang tersebut tidak akan memiliki nilai. Sinergi Agama Hindu dan budaya Bali telah tampak sejak masa prasejarah Bali. Dari tinggalan arkeologi ditemukan bahwa Bali telah mengadakan hubungan dengan India dan China. Pertumbuhan budaya Bali telah berlangsung dengan adanya pengaruh asing. Demikian pula ketika Agama Hindu dan Buddha dianut oleh masyarakat Bali. Agama Hindu hingga kini tampak sangat dominan dan memberi rona serta mewarnai budaya dan kehidupan masyarakat Bali. Walaupun demikian, kedatangan dan pengaruh Agama Buddha, Kong Hu Chu, Tao juga kepercayaan masa prasejarah bersinergi dengan pertumbuhan budaya Bali. Sejak keruntuhan Majapahit di Jawa Timur, Bali mampu mempertahankan identitas budayanya. Agama Islam turut pula memberi warna dalam perkembangan kebudayaan Bali. Pada masa penjajahan Belanda, para misionaris Kristen (Katolik dan Protestan) juga mengembangkan sayapnya di Bali yang berlanjut dengan pergerakkan kebangsaan, yang kemudian diikuti dengan tumbuh dan berkembang nasionalisme Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Bali semakin mampu menunjukkan jati dirinya dan budaya Bali mulai tampil di berbagai belahan dunia seperti telah dijelaskan di atas. Dewasa ini, sinergi Agama Hindu dan budaya Bali menghadapi tantangan global, tantangan materialisme, dan bahkan hedonisme yang tentunya memberi dampak terhadap agama-agama dan kebudayaan Bali. Bagaimana proses sinergi Agama Hindu dengan budaya Bali dan bagaimana budaya Bali menghadapi tantangan globalisasi tersebut akan dibahas dalam tulisan ini. Karakteristik Agama Hindu Dipakai nama Hindu Dharma sebagai nama Agama Hindu menunjukkan bahwa kata Dharma mempunyai pengertian yang jauh lebih luas dibandingkan dengan pengertian kata agama dalam bahasa Indonesia. Dalam kontek pembicaraan kita saat ini pengertian Dharma disamakan dengan agama. Jadi Agama Hindu sama dengan Hindu Dharma. Kata Hindu sebenarnya adalah nama yang diberikan oleh orang-orang Persia yang mengadakan komunikasi dengan penduduk di lembah sungai Sindhu dan ketika orang-orang Yunani mengadakan kontak dengan masyarakat di lembah sungai Sindhu mengucapkan Hindu dengan Indoi dan kemudian orang-orang Barat yang datang kemudian menyebutnya dengan India. Pada mulanya wilayah yang membentang dari lembah sungai Sindhu sampai yang kini bernama Srilanka, Pakistan, Bangladesh dan bahkan Bharata yang disebut juga Jambhudvipa. Nama asli dari agama ini adalah Sanatana Dharma atau Vaidika Dharma. Kata Sanatana Dharma berarti agama yang bersifat abadi dan akan selalu dipedomani oleh umat manusia sepanjang masa, karena ajaran yang disampaikan adalah kebenaran yang bersifat universal, merupakan santapan rohani dan pedoman hidup umat manusia yang tentunya tidak terikat oleh kurun waktu tertentu. Kata Vaidika Dharma berarti ajaran agama yang bersumber pada kitab suci Veda, yakni wahyu Tuhan Yang Maha Esa (Mahadevan,1984:13). Kitab suci Veda merupakan dasar atau sumber mengalirnya ajaran Agama Hindu. Para rsi atau maharsi yakni orang-orang suci dan bijaksana di India zaman dahulu telah menyatakan pengalaman-pengalaman spiritual-intuisi mereka (Aparoksa-Anubhuti) di dalam kitab-kitab Upanisad, pengalaman-pengalaman ini sifatnya langsung dan sempurna. Hindu Dharma memandang pengalaman-pengalaman para maharsi di zaman dahulu itu sebagai autoritasnya. Kebenaran yang tidak ternilai yang telah ditemukan oleh para maharsi dan orang-orang bijak sejak ribuan tahun yang lalu, membentuk kemuliaan Hinduisme, oleh karena itu Hindu Dharma merupakan wahyu Tuhan Yang Maha Esa (Sivananda, 1988: 4). Kebenaran tentang Veda sebagai wahyu Tuhan Yang Maha Esa ditegaskan oleh pernyataan yang terdapat dalam kitab Taittiriya Aranyaka 1.9.1 (Dayananda Sarasvati, 1974: LI), maupun Maharsi Aupamanyu sebagai yang dikutip oleh maharsi Yaska (Yaskacarya) di dalam kitab Nirukta II.11 (Dayananda Sarasvati, 1974:LI). Bagi umat Hindu kebenaran Veda adalah mutlak, karena merupakan sabda Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Sri Chandrasekarendra Sarasvati, pimpinan tertinggi Sankaramath yakni perguruan dari garis lurus Sri Sankaracarya menegaskan: �Dengan pengertian bahwa Veda merupakan sabda Tuhan Yang Maha Esa (Apauruseyam atau non human being) maka para maharsi penerima wahyu disebut Mantradrastah (mantra drastah iti rsih). Puruseyam artinya dari manusia. Bila Veda merupakan karangan manusia maka para maharsi disebut Mantrakarta (karangan/buatan manusia) dan hal ini tidaklah benar. Para maharsi menerima wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa (Apauruseyam) melalui kemekaran intuisi (kedalaman dan pengalaman rohaninya), merealisasikan kebenaran Veda, bukan dalam pengertian mengarang Veda. Apakah artinya ketika seorang mengatakan bahwa Columbus menemukan Amerika? Bukankah Amerika telah ada ribuan tahun sebelum Columbus lahir ? Einstein, Newton atau Thomas Edison dan para penemu lainnya menemukan hukum-hukum alam yang memang telah ada ketika alam semesta diciptakan. Demikian pula para maharsi diakui sebagai penemu atau penerima wahyu tuhan Yang Maha Esa yang memang telah ada sebelumnya dan karena penemuannya itu mereka dikenal sebagai para maharsi agung. Mantra-mantra Veda telah ada dan senantiasa ada, karena bersifat Anadi-Ananta yakni kekal abadi mengatasi berbagai kurun waktu. Oleh karena kemekaran intuisi yang dilandasi kesucian pribadi mereka, para maharsi mampu menerima mantra Veda. Para maharsi penerima wahyu Tuhan Yang Maha Esa dihubungkan dengan Sukta (himpunan mantra), Devata (Manifestasi Tuhan Yang Maha Esa yang menurunkan wahyu) dan Chanda (irama/syair dari mantra Veda). Untuk itu umat Hindu senantiasa memanjatkan doa pemujaan dan penghormatan kepada para Devata dan maharsi yang menerima wahyu Veda ketika mulai membaca atau merapalkan mantra-mantra Veda (Chandrasekharendra, 1988:5). Kitab suci Veda bukanlah sebuah buku sebagai halnya kitab suci dari agama-agama yang lain. Kitab ini terdiri dari beberapa buku yang terdiri dari 4 kelompok yaitu kitab-kitab Mantra (Samhita) yang dikenal dengan Catur Veda (RIgveda, Yajurveda, Samaveda atau Atharvaveda). Masing-masing kitab mantra ini memiliki kitab-kitab Brahmana, Aranyaka dan Upanisad) yang seluruhnya itu diyakini sebagai wahyu wahyu Tuhan Yang Maha Esa yang didalam bahasa Sanskerta disebut Sruti. Kata Sruti berarti sabda Tuhan Yang Maha Esa yang didengar oleh para maharsi. Pada mulanya wahyu itu direkam melalui kemampuan mengingat dari para maharsi dan selalu disampaikan secara lisan kepada para murid dan pengikutnya, lama kemudian setelah tulisan (huruf) dikenal selanjutnya mantra-mantra Veda itu dituliskan kembali. Seorang maharsi agung, yakni Vyasa yang disebut Krisndvaipayana dibantu oleh para muridnya menghimpun dan mengkompilasikan mantra-mantra Veda yang terpencar pada berbagai Sakha, ASrama (ashram), Gurukula, Sampradaya, Parampara atau Akara. Di dalam memahami ajaran Agama Hindu, disamping kitab suci Veda (Sruti) yakni wahyu Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber tertinggi, dikenal pula hiarki sumber ajaran Agama Hindu yang lain yang merupakan sumber hukum Hindu adalah Smriti (kitab-kitab DharmaSastra atau kitab-kitab hukum Hindu), Sila (yakni tauladan pada maharsi yang termuat dalam berbagai kitab Itihasa (sejarah) dan Purana (sejarah kuno), Acara (tradisi yang hidup pada masa yang lalu yang juga dimuat dalam berbagai kitab Itihasa (sejarah) dan Atmanastusti, yakni kesepakatan bersama berdasarkan pertimbangan yang matang dari para maharsi dan orang-orang bijak yang dewasa ini diwakili oleh majelis tertinggi umat Hindu dan di Indonesia disebut Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat yang dipresentasikan dengan kedudukan Sabha Pandita sebagai organ tertinggi Parisada, sedang Pengurus Harian adalah sebagai ekskutan yang bila melanggar AD/ART dapat diberhentikan oleh Sabha Pandita. Majelis yang dipresentasikan oleh Sabha Pandita inilah yang berhak mengeluarkan Bhisama (semacam fatwa) bilamana tidak ditemukan sumber atau penjelasannya di dalam sumber-sumber ajaran Hindu yang kedudukannya lebih tinggi. Hindu Dharma memperkenalkan kemerdekaan mutlak terhadap pikiran rasional manusia. Hindu Dharma tidak pernah menuntut sesuatu pengekangan yang tidak semestinya terhadap kemerdekaan dari kemampuan berpikir, kemerdekaan dari pemikiran, perasaan dan pemikiran manusia. Ia memperkenalkan kebebasan yang paling luas dalam masalah keyakinan dan pemujaan. Hindu Dharma adalah suatu agama pembebasan. Ia memperkenalkan kebebasan mutlak terhadap kemampuan berpikir dan perasaan manusia dengan memandang pertanyaan-pertanyaan yang mendalam terhadap hakekat Tuhan Yang Maha Esa, jiwa, penciptaan, bentuk pemujaan dan tujuan kehidupan ini. Hindu Dharma tidak bersandar pada satu doktrin tertentu ataupun ketaatan akan beberapa macam ritual tertentu maupun dogma-dogma atau bentuk-bentuk pemujaan tertentu. Ia memperkenalkan kepada setiap orang untuk merenungkan, menyelidiki, mencari dan memikirkannya, oleh karena itu, segala macam keyakinan/Sraddha, bermacam-macam bentuk pemujaan atau Sadhana, bermacam-macam ritual serta adat-istiadat yang berbeda, memperoleh tempat yang terhormat secara berdampingan dalam Hindu Dharma dan dibudayakan serta dikembangkan dalam hubungan yang selaras antara yang satu dengan yang lainnya. Tentang kemerdekaan memberikan tafsiran terhadap Hindu Dharma di dalam Mahabharata dapat dijumpai sebuah pernyataan : "Bukanlah seorang maharsi (muni) bila tidak memberikan pendapat terhadap apa yang dipahami" (Radhakrishnan, 1989:27). Inilah salah satu ciri atau karakteristik dari Hindu Dharma. Karakteristik atau ciri khas lainnya yang merupakan barikade untuk mencegah berbagai pandangan yang memungkinkan tidak menimbulkan pertentangan di dalam Hindu Dharma adalah Adikara dan Ista atau Istadevata. Adikara berarti kebebasaan untuk memilih disiplin atau cara tertentu yang sesuai dengan kemampuan dan kesenangannya, sedangkan Ista atau Istadevata adalah kebebasan untuk memilih bentuk Tuhan Yang Maha Esa yang dijelaskan daalam kitab suci dan susatra Hindu, yang ingin dipuja sesuai dengan kemantapan hati. Svami Sivananda, seorang dokter bedah yang pernah praktek di Malaya (kini Malaysia) kemudian meninggalkan profesinya itu menjadi seorang Yogi besar dan rohaniawan agung pendiri Divine Life Society menyatakan: Hindu Dharma sangatlah universal, bebas, toleran dan luwes. Inilah gambaran indah tentang Hindu Dharma. Seorang asing merasa terpesona keheranan apabila mendengar tentang sekta-sekta dan keyakinan yang berbeda -beda dalam Hindu Dharma; tetapi perbedaan-perbedaan itu sesungguhnya merupakan berbagai tipe pemahaman dan tempramen, sehingga menjadi keyakinan yang bermacam-macam pula. Hal ini adalah wajar. Hal ini merupakan ajaran yang utama dari Hindu Dharma; karena dalam Hindu dharma tersedia tempat bagi semua tipe pemikiran dari yang tertinggi sampai yang terendah, demi untuk pertumbuhan dan evolusi mereka (Sivananda,1988:134). Sejalan dengan pernyataan ini Max Muller mengatakan bahwa Hindu Dharma mempunyai banyak kamar untuk setiap keyakinan dan Hindu Dharma merangkum semua keyakinan tersebut dengan toleransi yang sangat luas dan Dr. K.M. Sen mengatakan bahwa dengan definisi Hinduisme menimbulkan kesulitan lain. Agama Hindu menyerupai sebatang pohon yang tumbuh perlahan dibandingkan sebuah bangunan yang dibangun oleh arsitek besar pada saat tertentu. Pernyataan-pernyataan diatas adalah benar sebab dalam ajaran Agama Hindu dikenal banyak jalan atau cara mencapai Brahman, Tuhan Yang Maha Esa dengan ribuan Udbhava (manifestasi) Nya dengan nama-Nya berbeda-beda. Tuhan Yang Maha Esa, melalui Avatara-Nya Sri Bhagavan Krisna dalam kitab suci Bhagavadgita (IV.7) secara tegas menyatakan . Quote:
Walaupun karakteristik ajaran Hindu Dharma sebagai telah diuraikan di atas, tidaklah berarti ajaran Agama Hindu itu tidak jelas dan menafsirkannya di luar kewenangan dan jangkauan kitab suci. Memang kelihatan demikian banyaknya variasi di dalam Hindu Dharma, namun sesungguhnya ajarannya dimana-mana dan kapan saja sama. Essensi ajaran Hindu Dharma yang bersumber dan mengalir dari kitab suci Veda dengan susatra Hindu lainya yang ditulis dalam berbagai bahasa dirumuskan dalam ajaran Sraddha (Tattva) atau keimanan, dilaksanakan dan diejawantahkan dalam prilaku Tata SuSila atau budi pekerti berdasarkan ajaran Dharma dan ekspresinya nampak pada dalam Acara Agama. Bersambung ke Post Berikutnya |
Lanjutannya.. Ajaran Sraddha yang merupakan dasar keimanan Hindu Dharma dirumuskan dalam Pa�ca Sraddha, yakni keyakinan terhadap Brahman, para dewa manifestasi-Nya dan Avatara-Nya, keyakinan terhadap kebenaran Atman, roh atau jiva yang menghidupkan semua mahluk dan Atman merupakan percikan-Nya (Brahman/Tuhan Yang Maha Esa) Yang Trancendent maupun Yang Immanet. Sraddha, keyakinan atau keimanan yang ketiga adalah terhadap kebenaran adanya Karmaphala (hukum perbuatan), keimanan yang keempat adalah keyakinan terhadap penjelmaan kembali, Samsara (rebith) dan yang kelima adalah Moksa, yakni kebebasan tertinggi yang mesti dicapai umat manusia, bersatunya Atman dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa.
Ajaran Hindu Dharma tidaklah ada artinya bila tidak diamalkan oleh pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana seharusnya sebagai mahluk individu, sosial yang hidup bersama menikmati kemurahan bunda pertiwi bersama makhluk hidup lainnya. Semuanya itu dijelaskan dalam ajaran tata susila Hindu Dharma, yang merupakan pedoman yang harus dilakoni oleh setiap umat. Aspek Acara sangat komplek menyangkut berbagai aktivitas keagamaan terutama bidang ritual dengan berbagai kaitannya dan hal ini oleh karena sifatnya berbagai bentuk atau wujud pengalaman ajaran yang kasat mata, maka faktor lingkungan alam dan budaya yang menekankan keharmonisan memberikan rona dan mewarnai perbedaan-perbedaan praktek-praktek ritual/keagamaan. Demikianlah keanekaragaman dalam bentuk luarnya, namun memiliki satu keragaman dan satu tujuan mewujudkan kesejahtraan jasmani dan rohani serta bersatunya Atman dengan Brahman. Kalimat ini kemudian diformulasikan dan dijadikan motto oleh Sri Ramakrishna Mission, sebagai berikut. Quote:
Mewujudkan Jagadhita (kesejahtraan lahiriah) dan Moksa (kebahagian yang sejati) adalah tujuan Hindu Dharma dan juga sekaligus pula tujuan hidup manusia. Dari formulasi di atas, kemudian dikenal tujuan Agama Hindu yang dirumuskan dalam kalimat: moksartham jagadhitaya iti dharmah, yang maknanya melalui ajaran agama untuk mencapai jagadhita dan moksa. Ajaran Agama Hindu bagaikan aliran sungai mengaliri berbagai budaya dan peradaban umat manusia, sejak diturunkan oleh-Nya di lembah sungai Sindhu hingga ke Indonesia dan Bali khususnya, agama ini menyuburkan lembah-lembah kehidupan, peradaban dan budaya umat manusia yang dilalui itu. Agama Hindu menjadi jiwa dari segala aktivitas pemeluknya serta peradaban dan budaya yang mereka anut. Menyatunya antara agama dan budaya, seperti jalinan benang tenun (kain endek Bali), yang menyatu sedemikian rupa dengan keindahannya yang mempesona. Di setiap wilayah yang dialiri oleh ajaran agama Hindu terjadi sinergi yang mempelihatkan identitas budayanya masing-masing, oleh karena itu akan tampak dalam acara Agama Hindu di masing-masing daerah, baik di India (tampak berbeda pelaksananan Agama Hindu di India Utara, Selatan, Barat, dan lain-lain karena faktor budaya pendukung agama tersebut), demikian pula di Indonesia, tampak perbedaan antara Agama Hindu yang dipeluk oleh warga Dayak Kaharingan, Hindu yang dipeluk oleh masyarakat Jawa dan sebagainya yang semuanya memiliki identitas budayanya masing-masing yang memberi warna budaya agama yang berbeda-beda. Masa Prasejarah Bali sebagai sebuah pulau kecil di hamparan katulistiwa Nusantara sejak masa prasejarah ikut serta dalam pertumbuhan budaya yang menjadi akar dari perkembangan kebudayaan nasional. Penelitian arkeologi yang selama ini dilakukan di Bali telah berhasil mengungkapkan awal hubungan daerah ini dengan India. Di situs Sembiran telah ditemukan puluhan fragmen gerabah India dengan pola hias rolet, dua buah fragmen tepian gerabah Arikamedu (India) tipe 10, dua buah tepian gerabah tepian Arikamedu tipe 18, sebuah gerabah Arikamedu tipe 141, dan sebuah batu bertulis dengan huruf Kharoshti atau Brahmi. Selain itu, ratusan pecahan gerabah yang dipoles dengan warna hitam kemungkinan juga berasal dari India karena mempunyai kandungan kimiawi dan mineral yang sama dengan gerabah berpola hias rolet tersebut. Perlu dicatat bahwa situs Sembiran dan Pacung di Bali Utara telah menghasilkan temuan gerabah India terbanyak sampai saat ini di Asia Tenggara. Kronologi gerabah India di Sembiran mungkin berasal dari awal abad Masehi atau sekitar 2.000 tahun yang lalu (Ardika, 1997:62). Pada masa bercocok tanam, dengan memperhatikan tipologi tinggalan beliung persegi di Bali, maka dapat dikatakan bahwa Bali pada masa itu telah mempunyai hubungan budaya yang luas dengan daerah lainnya di kepulauan Indonesia maupun di Asia Tenggara (di antaranya Malaysia, Burma, Kamboja, Thailand, Laos, dan bahkan dengan China dan Formosa). Hubungan yang demikian luas terjadi akibat adanya migrasi yang disebabkan oleh pencarian daerah yang lebih subur untuk kepentingan perladangan. Hal ini ditunjang oleh kamajuan teknologi alat-alat batu dengan beberapa macam tipologi yang dapat dipergunakan dalam pekerjaan khusus seperti pembuatan perahu sebagai alat transportasi laut dalam penyeberangan dari pulau ke pulau lain di kawasan Asia Tenggara (Suastika, 1997:38). Sejalan dengan penelitian Suastika di atas, kini kepemilikan tanah di Desa Catur, Kintamani, Bangli lebih banyak dimiliki oleh etnis China yang memang mereka diduga telah datang ke Bali pada masa pertama kalinya terjadi hubungan antara Bali dengan China. Di Desa Catur, hingga kini diwarisi adanya pemujaan versi China yang di tempatkan di komplek Pura Desa di desa tersebut. Oleh umat Hindu setempat disebut sebagai tempat memuja Ratu Subandar. Hal yang sama dapat dijumpai di Pura Balingkang, Pura Ulundanu Batur, Kintamani, dan Pura Penataran Agung Besakih. Rupanya sejak zaman prasejarah Bali masyarakat Bali telah bersinergi dengan etnis luar (khususnya China). Demikian pula pada masa perundagian. Masa perundagian adalah puncak segala kemajuan yang berhasil dicapai yakni merupakan perkembangan lebih lanjut dari masa bercocok tanam. Penduduk yang hidup bergabung dalam suatu desa, sudah berhasil mencapai suatu taraf yang baik dengan penguasaan teknologi yang tinggi seperti teknik pembuatan gera�bah, kepandaian menuang perunggu. Masa perundagian telah menghasilkan kebudayaan Indonesia asli yang bernilai tinggi ka�rena dijiwai oleh konsepsi alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat pada waktu itu (Putra, 1987:50). Kepandaian menuang benda-benda perunggu yang dibentuk menjadi bermacam-macam benda yang diinginkan, dapat disebut�kan sebuah di antaranya yang ditemukan di Bali yang kini disim�pan di Pura Penataran Sasih Pejeng, Gianyar yakni oleh masyarakat dinamakan �Bulan Pejeng� atau Nekara. Pembuatan Nekara ini dengan cara cire perdue atau cetakan hilang. Namun, yang perlu diperhatikan di sini adalah fungsi benda tersebut se�bagai benda upacara keagamaan seperti upacara untuk mohon hujan, di samping ditemukannya hiasan kodok pada bagian bidang pukul�nya dan juga sebagai genderang perang. (Putra, 1987:51, Ardana, 1982:50). Pada masa perundagian seni pahat sudah berkembang dengan baik, terbukti dari pola hias kedok muka pada tonjolan beberapa sarkofagus serta arca-arca sederhana dari beberapa desa di Bali. Kemungkinan besar bahwa seni pahat dari masa perundagian inilah selanjutnya menjadi dasar bagi perkembangan seni pahat di Bali setelah Agama Hindu sampai di daerah ini (Darsana, 1997:25). Sejalan dengan pandangan tersebut maka kepercayaan dan budaya pada masa prasejarah Bali merupakan landasan masuk dan berkembangnya Agama Hindu dan pertumbuhan kebudayaan Bali. Perkembangan Agama Hindu dan Buddha di Bali 1 Tentang sejarah perkembangan agama Hindu di Bali, seperti diungkapkan oleh Swellengrebel (1960:17) sumber utamanya adalah prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para raja yang banyak jumlahnya baik yang tertulis pada batu maupun pada logam (tembaga). Prasasti-prasasti itu menceritakan para raja yang memerintah dan para menterinya, hubungannya dengan administrasi pemerintahan pusat dan orang-orang di desa-desa, peraturan di bidang keagamaan, aturan yang berhubungan dengan pengairan, perpajakan, dan sebagainya. Sumber lainnya adalah peninggalan purbakala, arca-arca dan artifak-artifak. Berdasarkan ungkapan Swellengrebel di atas maka kehidupan keagamaan di Bali dapat dikaji melalui sumber-sumber tersebut di atas. Hubungan Bali atau Nusantara dengan India di masa yang silam dapat diketahui dari kitab Ramayana karya Maharsi Valmiki, pada Kiskindhakan�a (XL.30) menyebutkan nama Javadvipa dan Saptarajya, yang menurut Nabin Chandra Das (Widnya, 2001) Saptarajya adalah tujuh tempat, yaitu Suvarnadvipa (Sumatra), Kalimantan (Borneo), Sulawesi (Celebes), Irian Jaya (West New Guinea), Bali, Java, dan Malaya (Misra,1989: VI). Hubungan antara India dengan Bali diungkapkan pula oleh Sarkar (Phalgunadi, 1991:33) termuat dalam kitab Brihatsamhita dan Kathasaritsagara yang membuktikan sudah adanya kontak antara Bali dengan India dalam bidang perdagangan dan agama. Kedua buku di atas menyebutkan nama Bali sebagai Narikeladvipa. Menurut Damais yang dimaksud dengan Bhumi Narikela adalah Pulau Bali yang menurut anggapannnya dapat dibuktikan dari sejumlah prasasti yang ditemukan di pulau ini. Banyak prasasti Bali yang menyebutkan Bali sebagai pulau kelapa. Prasasti Poh (tahun 905 Masehi) menyebutkan �vanua ri rumaksan ring nyu� yang berarti pulau kelapa. Weber (1974:202, 213) menyatakan Brihatsamhita ditulis oleh Varamihira pada abad ke-5 atau ke-6 Masehi dan Kathasaritsagara ditulis oleh Somadeva pada abad ke-11 Masehi. Di dalam kitab Ma�juSri Mulakalpa secara tegas disebutkan nama Pulau Bali. Kitab ini diduga ditulis pada abad ke-7 Masehi (Widnya, 2001:5) yang menunjukkan bahwa saat itu telah terjadi hubungan antara Bali dengan India. Agama Hindu dan Buddha dikenal sebagai agama yang berasal dari sumber yang sama. Tinggalan prasasti dan arkeologi menunjukkan kedua agama ini hampir bersamaan tiba di Bali. Berdasarkan fragmen prasasti yang ditemukan di Pejeng, Gianyar, Agama Hindu sekta Saiva (Saivapaksa) diduga berkembang pada abad ke-8 Masehi. Fragmen prasasti ini ditulis memakai bahasa Sanskerta dan bila dibandingkan dengan stempel tanah liat yang berisi mantram agama Buddha yang disebut dengan ye-te mantra..... rupanya sezaman sehingga diduga berasal dari tahun 778 Masehi. Pada baris pertama dari prasasti tersebut tertulis: �Sivas.....ddh..... yang tidak mungkin berarti Sivasiddhanta (Ardana, 1982:20). Data lainnya yang juga dapat menunjukkan sekta Saiva berkembang di Bali pada abad ke-8 Masehi adalah peninggalan purbakala, yakni berupa sebuah arca yang disebut arca Siva yang ditemukan pada sebuah pura bernama Putra Bhattara Desa di Desa Bedahulu (Sttuterheim, 1935:35). Arca ini berasal dari periode Hindu-Balinese Art, yakni dari abad ke-8 Masehi, pada saat yang bersamaan juga ditemukan arca Siva pada beberapa candi di kompleks Candi Dieng, Jawa Tengah (Kempers, 1959: 31). Data yang lebih autentik adalah data prasasti Sukawana A I yang berasal dari tahun 882 Masehi, yakni menyebutkan tiga tokoh agama, yaitu: bhiksu (pandita Buddha) Siva Kangsita, Siva Nirmala, dan Sivapraj�a yang membangun pertapaan di puncak gunung Cintamani (Goris, I, 1954: 53). Di sini tidak dijelaskan agama yang dipeluk oleh ketiga pandita itu. Oleh karena ada kata bhiksu yang menunjukkan pandita Buddha dan nama Siva atau barangkali kedua agama itu disatukan (Sivabuddha) seperti pada masa pemerintahan Raja Udayana, karena sejak abad ke-10 Masehi kedua agama itu, yakni Siva dan Buddha menjadi agama negara (agama resmi)(Ardana, 1982:21). Menurut Goris (1960:98), kedatangan Agama Hindu di Bali dalam dua bentuk, yakni dalam bentuk agama yang dibawa oleh para pandita (priestly religion) dan dalam bentuk kepustakaan (literature), khususnya dalam bentuk epik besar. Dalam epik besar ini, tidak semuanya sekta Saivasiddhanta, tetapi dapat diketahui dan diakui adanya tiga Dewa Brahma, Siva dan Visnu meskipun dalam epik itu ada yang spesifik, yaitu penekanan kepada Sivaistik dan Visnuistik. Dari kepustakaan tersebut diketahui akar dari hukum-hukum dan orang Bali mengetahui ajaran Agama Hindu. Dalam epik Agama Hindu ditemukan banyak Dewa (Brahma dengan Saktinya Sarasvati, Siva dengan Durga, Visnu dengan Sri dan juga Ganesa, Dewa-Dewa yang populer dalam epik), banyak raksasa, dan roh-roh jahat. Di samping itu, terdapat penjelasan tentang persembahan, tempat-tempat pemujaan, dan kalender untuk menentukan waktu penyelenggaraan upacara. Selain itu, juga terdapat upacara-upacara untuk keperluan rumah tangga, upacara pembakaran jenasah (kremasi) bagi orang yang meninggal, upacara siklus hidup dari sejak lahir sampai mati, arti upacara-upacara, dan juga persembahan yang besar. Dalam hal ini Agama Hindu banyak berhubungan dengan ajaran agama asli orang Bali, sehingga merupakan daya tarik bagi orang Bali untuk menjadi penganut Agama Hindu-Bali yang baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Goris, seperti tersebut di atas, maka kedatangan Agama Hindu yang dibawa oleh para pandita sangat memungkinkan untuk mendapat dukungan sepenuhnya dari raja-raja Bali yang berkuasa pada masa yang silam. Hal ini terbukti hingga kini masih tampak peranan pandita istana (purohita atau bhagawanta) sangat menentukan dalam kaitannya dengan upacara Yajna yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Demikian pula dalam pengembangan susastra Hindu, peranan raja tidak kalah pentingnya. Perkembangan susastra Hindu di Bali, baik dengan media bahasa Jawa Kuna dan Tengahan maupun sastra Bali hingga kini masih berlangsung. Bersambung ke post berikutnya |
Lanjutannya.. Dari penelitiannya terhadap 4 raja yang berkuasa pada masa Bali Kuna, Semadi Astra (1997:280) menemukan ada 16 orang pemuka agama Siva dan 12 orang pemuka agama Buddha, sebagai berikut.
Pemuka Agama Siva 1. Mpukwing Dharmahanyar 2. Mpukwing Hyang Padang 3. Mpukwing Binor 4. Mpukwing Mpukwing Lokeswara 5. Mpukwing Banyu Garuda 6. Mpukwing Makarun 7. Mpukwing Antakunyarapada 8. Mpukwing Udayalaya 9. Mpukwing Kanya 10. Mpukwing Kusumahajika 11. Mpukwing Kusumadanta (Puspadanta) 12. Mpukwing Kunjarapada 13. Mpukwing Pasabhan 14. Mpukwing Sikharadwara 15. Mpukwing Hyang karampas 16. Samgat Juru Wadwa Pemuka Agama Buddha 1. Mpukwing Kutihanyar 2. Mpukwing Canggini 3. Mpukwing Bajrasikhara 4. Mpukwing Kadhiran 5. Mpukwing Dharmaryya 6. Mpukwing Waranasi 7. Mpukwing Barabahung 8. Mpukwing Karana 9. Mpukwing Raganagara 10. Mpukwing Purwanagara 11. Mpukwing Nalnyja 12. Samgat Mangirengngireng Wandami Berdasarkan jumlah pemuka agama yang tersebut dalam jabatan pemerintahan empat raja pada zaman Bali Kuna di atas, dapat dinyatakan bahwa pemeluk Agama Hindu lebih banyak dibandingkan dengan agama Buddha. Mengenai bangunan suci terkait dengan kedua agama di atas, sumber prasasti hanya menyebut beberapa istilah, seperti satra, patapan, hyang, vihara, sima, sala, kaklungan, pendem, kamulan, meru, dan sebagainya. Di antara nama-nama tersebut, wihara jelas merupakan pesanggrah�an bagi para pendeta Buddha, hyang singkatan dari istilah kahyangan yang berarti tempat suci. Sampai sekarang di Bali tiga buah pura di tiap-�tiap desa pakraman (desa adat) disebut Kahyangan Tiga, yaitu Pura Desa, Puseh, dan Dalem. Patapan merupakan tempat untuk bertapa. Sima merupakan daerah perdikan yang tugasnya memelihara bangunan suci yang ada di daerah itu. Kamulan rupa-rupanya masih tertinggal menjadi sanggah kamulan di Bali yang sekarang berfungsi sebagai tempat penghormatan roh suci leluhur. Meru merupakan bangunan suci berbentuk atap tumpang terbuat dari ijuk2. Perlu ditegaskan kembali bahwa pengaruh Jawa sangat besar di Bali sejak ibu Airlangga (Mahendradattagunapriyadharmapatni) sebagai raja yang amat berkuasa di Bali. Prasasti-prasasti yang diterbitkan sebelumnya berbahasa Bali Kuno yang bercampur dengan bahasa Jawa Kuno, maka sejak tahun 1.022 semua prasasti murni menggunakan bahasa Jawa Kuno (Satyawati, 1978:44). Dalam bidang susastra sejak pengaruh Hindu masuk ke Bali, pada mulanya tampak pengaruh bahasa Sanskerta dan Bali kuno, namun perkembangan berikutnya pengaruh bahasa Jawa Kuno atau Kawi sangat mendominasi, seperti dinyatakan oleh T. Goudriaan (1980:31) berikut. Quote:
Di lain pihak, selain dominasi susastra Jawa Kuno seperti tersebut di atas, I Made Suastika menyatakan bahwa pada abad ke-18 (zaman Kerajaan Klungkung) karya sastra Jawa Kuno dan Pertengahan digubah dalam genre baru yang disebut parikan atau gaguritan (1995:30), maka sekitar abad ke-17 sampai dengan abad ke-19 teks-teks baik berbentuk kidung atau gaguritan sudah sangat populer di antaranya karya sastra berupa Kidung Panji Amalatrasmi, Gaguritan Bhimasvarga, Kidung Bagus Diarsa dan lain-lain disusun oleh para sastrawan pada zaman tersebut yang memberi pemahaman tentang Agama Hindu bagi masyarakat Bali. Aktivitas memahami susastra Jawa Kuno hingga saat ini masih dilestarikan melalui Dharmagita atau Pesantian-Pesantian yang ada hampir di seluruh Desa Pakraman di Bali. Di Bali yang dimaksud dengan susastra Bali tidak lain adalah sebagian besar susastra Jawa Kuno dan sebagian kecil susastra berbahasa Bali, menunjukkan bahwa budaya Bali menyerap budaya Jawa Kuno yang sumbernya adalah budaya India. Dilihat dari seni arca, karakter arca dalam periode Hindu Bali (periode pertama Hindu masuk ke Bali) terlihat lemah lembut, kegemuk-gemukan, bersikap tenang, mata setengah terbuka, pandangan mengarah ke ujung hidung. Ciri-ciri arca �semacam ini dapat dijumpai dalam stupika-stupika tanah liat yang banyak didapatkan di sekitar desa Pejeng, Tatiapi, dan Blahbatuh tetapi arca ini bersifat Buddhist. Untuk arca Hindu dapat dicontohkan arca Siwa yang terdapat di Pura Putra Bhatara Desa Bedulu. Kecuali arca Siwa tersebut, arca Hindu lainnya, belum ditemukan tinggalannya. Konteksnya dengan daerah lain, tak dapat dipungkiri bahwa seni arca di Bali saat itu mendapat pengaruh seni klasik Jawa Tengah. Ciri-ciri kelemahlembutan, kegemukan, dan lain sebagainya seperti tersebut di atas adalah ciri-ciri arca klasik Jawa Tengah. Akan tetapi arca yang berciri demikian bukan saja didapatkan di Jawa dan Bali, tetapi juga di Kamboja, Thailand, Bhirma, dan Malaysia. Karena itulah maka arca-arca masa klasik Jawa Tengah disebut memiliki �Gaya Intemasional�, dan pusat persebarannya diduga di Nalanda (Redig, 1997:172). Berdasarkan uraian tersebut di atas, awal mulanya pengaruh Hindu di Bali dari seni arca masih menampakkan gaya internasional atau gaya asli India. Dalam perkembangan berikutnya, utamanya bentuk arca perwujudan tampak kaku, seperti pula halnya di Jawa Timur. Dalam seni ukir yang diwarisi dewasa ini, tampak pula pengaruh China, Arab, dan Belanda seperti patra (lukisan atau ukiran daun), di antaranya: Patra China, Patra Mesir, dan Patra Welanda. Dalam seni tari, tari-tarian yang terdapat pada masa Bali Kuno tampak hingga kini masih lestari, di antaranya adalah Partapukan yang kini dikenal dengan tari topeng, Abanwal yang dikenal dengan lawak. Demikian pula beberapa jenis gamelan masih berkelanjutan diwarisi kini di Bali3. Apakah di kemudian hari akan muncul lukisan atau ukiran patra sebagai pengaruh dari negara lain seperti Amerika Serikat atau Amerika Latin? Perkembangan dan dinamika budaya Bali yang akan menjawabnya. Bersambung di post berikutnya |
Lanjutannya.. Senergi Agama-Agama dan Kebudayaan Bali
Kata sinergi (synergy) dalam The New Lexicon Webster International Dictionary of The English Language (1976:996) dinyatakan sebagai: cooperation, working together, combined action, the cooperative action of two or more parts or organs of the the body; the cooperative interaction of different drugs. Berdasarkan uraian sebelumnya maka Agama Hindu sangat dominan pengaruh atau sinerginya dengan kebudayaan Bali dibandingkan dengan agama-aqgama lainnya. Untuk mengetahui bagaimana kebudayaan Bali (masa prasejarah) mendapat pengaruh dari Agama Hindu (yang mengantarkan memasuki masa sejarah) kiranya dapat dilihat melalui kerangka tentang unsur-unsur kebudayaan seperti yang diajukan oleh C. Kluckhohn dalam karangannya Universal Categories of Culture (1953) seperti yang disetujui oleh Koentjaraningrat (1980:217) yang terdiri dari: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Pengaruh Agama Hindu terhadap 7 unsur kebudayaan Bali dapat dijelaskan sebagai berikut. 1)Bahasa. Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Agama Hindu masuk ke Bali pada mulanya melalui media bahasa Sanskerta kemudian sejak pemerintahan Mahendradattagunapriyadharmapatni (permaisuri raja Dharmodayana Varmedeva), maka bahasa Jawa Kuno menggantikan media berbagai susastra Hindu dan hal ini tampak pengaruhnya terhadap bahasa Bali dewasa ini. Dalam mantra stuti masih menggunakan bahasa Sanskerta4. 2)Sistem pengetahuan. Melalui media bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno masyarakat Bali memiliki berbagai sistem pengetahuan yang bersumber dari Agama Hindu dan budaya India, antara lain sistem pengobatan (ausadha), pembangunan rumah (hastakosalakosali dan hastabhumi) dan lain-lain. 3)Organisasi sosial. Pada prasasti-prasasti Bali Kuno sebelumnya disebut adanya sistem pemerintahan serta adanya lembaga kerajaan yang disebut panglapuan, paramaksa, samohanda, dan senapati di panglapuan. Sejak tahun 1001 Masehi, lembaga tersebut dinamakan pakira-kira i jero makabehan yang anggotanya terdiri dari para senapati (panglima perang) dan para pandita Siva dan Buddha (Ardana, 1982:31), demikian pula sistem pemerintahan di pedesaan seperti adanya karaman, thani, dan dalam perkembangan selanjutnya di Bali dikenal adanya tipe desa kuno dengan sistem pemerintahnan Mauluapad dan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau para Punggawa. 4)Sistem peralatan hidup. Di samping sistem yang peralatan hidup yang merupakan produk asli Bali, sejak zaman prasejarah sudah pula memakai peralatan yang berasal dari luar, misalnya dapat dilihat dari tinggalan gerabah Arikamedu dari India Selatan yang rupanya sudah berlangsung sejak awal abad Masehi. 5)Sistem mata pencaharian. Pada masa prasejarah hingga dewasa ini rupanya pertanian yang kemudian berkembang dalam arti luas termasuk perkebunan walaupun merupakan hal yang sangat universal, pengaruh Agama Hindu tampak dari semua sistem pencaharian itu dikaitkan dengan Agama Hindu, artinya dalam memenuhi kebutuhan hidup senantiasa dikaitkan dengan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tampak hingga dewasa ini sistem pengairan yang sangat terkenal yakni Subak selalu dikaitkan dengan Agama Hindu, misalnya disetiap mata air dan di tempat pembagian air dibangun pura Ulunsui, Bedugul, dan sebagainya. 6)Sistem Religi. Ketika Agama Hindu masuk ke Bali, masyarakat Bali saat itu telah menganut kepercayaan kepada roh suci leluhur, adanya penguasa alam, dan gunung-gunung yang dianggap suci. Agama Hindu yang memiliki keyakinan (Sraddha) yang sama dengan kepercayaan setempat, yakni Pitrapuja (pemujaan kepada roh suci leluhur) mudah saja diterima oleh masyarakat Bali saat itu. Dan hal tersebut berlangsung hingga saat ini. Kedatangan Agama Hindu ke Bali tidak mengubah kepercayaan setempat tetapi memberikan pencerahan dengan lebih mengembangkan kepercayaan setempat. Pemujaan kepada penguasa tertinggi masyarakat Terunyan yakni Da Tonta berupa arca batu megalitik, dipermulia dengan menempatkan kata Bhattara pada nama sebelumnya dan kemudian disemayamkan pada bangunan Meru. Hal ini dapat diketahui antara lain dari prasasti Terunyan yang berasal dari 818 Saka (896 M), isinya tentang pemberian ijin kepada nanyakan pradhana dan bhiksu agar membangun sebuah kuil untuk Hyang Api di desa Banua Bharu. Prasasti lainnya berasal dari tahun 813 Saka (891 M) isinya tentang pemberian ijin kepada penduduk desa Turu�an untuk membangun kuil bagi Bhatara Da Tonta. Oleh karena itu mereka dibebaskan dari beberapa jenis pajak, tetapi mereka ini dikenakan sumbangan untuk kuil tadi. Beberapa jenis pajak harus dibayar setiap bulan Caitra dan Magha, pada hari kesembilan (mahanavami). Bila ada utusan raja datang menyembah (sembahyang) pada bulan Asuji, mereka harus diberi makanan dan sebagainya (Sartono, 1976:136). Dalam prasasti itu juga menyebutkan haywahaywan di magha mahanavami (Goris, 1954:56). Dalam bahasa Bali dewasa ini kata mahaywahaywa (dari kata mahayu-hayu) berarti merayakan. Haywahaywan di magha mahanavami berarti perayaan Magha Mahanavami. Di India Mahanavami identik dengan Dasara yakni hari pemujaan ditujukan kepada para leluhur (Dubois, 1981:569). Swami Sivananda (1991:8) mengidentikkan Dasara dengan Durgapuja yang dirayakan dua kali setahun, yakni Ramanavaratri atau Ramanavami pada bulan Caitra, dan Durganavaratri atau Durganavami pada bulan Asuji (September-Oktober). Perayaan ini disebut juga Wijaya Dasami atau Sraddha Wijaya Dasami (hari pemujaan kepada leluhur dan perayaan kemenangan selama sepuluh hari). Hari raya ini di Bali (dirayakan dua kali dalam setahun) dikenal dengan nama Galungan yang hakekatnya adalah Durgapuja atau Sraddha Vijaya Dasami (hari pemujaan kepada leluhur dan perayaan kemenangan selama sepuluh hari) yang dirayakan secara besar-besaran sejak Gunapriyadharmapatni di-dharma-kan sebagai Durgamahisasuramardhini di pura Kedharma Kutri, Blahbatuh, Gianyar5.Beberapa hari raya Hindu di India dipribhumikan ke dalam bahasa lokal antara lain Ayudhapuja di Bali disebut Tumpek Landep, Pasupatipuja disebut Tumpek Uye, dan Sankarapuja disebut Tumpek Pengarah. Yatra disebut Melis, Makiyis, atau Melasti dan beberapa persembahan seperti puja disebut daksina, jajan dari beras berlobang di India selatan disebut Kalimaniarem, di Bali disebut Kaliadrem6 dan sebagainya. Karena adanya persamaan dalam keyakinan dengan religi prasejarah, maka masyarakat Bali saat itu tidak kesulitan dalam memeluk Agama Hindu yang ajarannya telah terdokumentasi dalam bentuk tulisan atau dibawa oleh para pandita. 7)Sistem Kesenian. Sistem ini (kesenian Bali) walaupun tidak bisa dirunut asalnya secara pasti namun adanya pertunjukkan wayang kulit yang oleh Brandes disebut sebagai kesenian asli Indonesia, di India selatan kita jumpai seni yang disebut Kathakali yang mirip dengan wayang kulit yang dipentaskan baik malam maupun siang hari (seperti wayang lemah), demikian pula pementasan cerita Ramayana, dan Bhimakumara seperti disebutkan dalam prasasti Jaha di Jawa Tengah bersumber kepada Ramayana dan Mahabharata yang di India disebut Ramalila dan Mahabharatalila atau Krishnalila. Beberapa tari lepas di Bali tampak seperti Bharatnatyam di India. Dalam seni arsitektur, struktur bangunan yang disebut Meru dapat dijumpai di Nepal dan di India utara7. Berdasarkan uraian tersebut maka masuknya Agama Hindu di Bali tidak merusak atau melenyapkan kepercayaan atau kebudayaan, dan bahkan dalam hal tertentu sangat menghargai kepercayaan dan tradisi budaya masyarakat Bali. Demikian antara lain pengaruh atau sinergi Agama Hindu terhadap berbagai aspek atau unsur-unsur kebudayaan Bali yang demikian rupa seperti sulit dibedakan antara Agama Hindu dan kebudayaan Bali yang dapat digambarkan sebagai diagram berikut. Diagram di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: Agama Hindu sebagai titik sentral (pusat). Agama Hindu melalui sistem atau media bahasa, yakni (1) Bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno diterima dan dianut oleh masyarakat Bali. Demikian pula melalui media bahasa Sanskerta dan Jawa Kuno masyarakat Bali yang telah menganut Agama Hindu memperoleh (2) sistem pengetahuan. Selanjutnya diterapkan (3) sistem sosial dengan sebagian masih mempertahankan sistem prasejarah dan sebagian lagi mengambil alih atau bersumber pada nilai-nilai Agama Hindu8. (4) Sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan kelanjutan dari masa prasejarah dan berkembang pula pada zaman sejarah dengan mengadopsi nilai Agama Hindu, misalnya didirikan tempat pemujaan, arca-arca dan sebagainya. (5) Sistem mata pencaharian masyarakat Bali yang pada mulanya bertani dan berburu, setelah adanya hubungan dengan China dan India mendapat pengaruh dari kedua kebudayaan tersebut, terutama dalam perdagngan. Dalam perkembangannya di setiap tempat untuk memperoleh mata pencaharian didirikan tempat pemujaan yang kemudian dikenal sistem Subak dengan Pura Ulunsui, Pura Bedugul, dan di pasar dibangun Pura Melanting sebagai tempat memuja Dewi Sri Laksmi.(6) Sistem religi pada masa prasejarah dengan masuk dan diterimanya Agama Hindu, kepercayaan lama dicerahkan dan didominasi oleh ajaran Agama Hindu. Demikian pula (7) sistem kesenian, akar-akar kesenian yang sudah terdapat pada masa prasejarah dikembangkan dengan tema-tema yang terdapat di dalam Agama Hindu dengan tetap menghargai dan mensinergikan budaya sebelumnya. Ketujuh unsur kebudayaan di atas (lingkaran-lingkaran kecil) berada dalam lingkaran besar kebudayaan Bali dan mendapat pencerahan dan diabdikan kembali kepada keagungan Agama Hindu (lingkaran di tengah-tengah), dengan demikian terjadi jalinan yang sangat halus sehingga sulit membedakan antara Agama Hindu dan kebudayaan Bali. Persamaan antara religi prasejarah Bali dengan Agama Hindu dapat dilihat beberapa di antaranya melalui perbandingan berikut . Religi Prasejarah
Agama Hindu
Seperti telah disebutkan di atas, dilihat dari proses dan sejarah perkembangan agama-agama di Bali, Agama Hindu hampir bersamaan datangnya dengan Agama Buddha, demikian pula dengan Agama Kong Hu Chu atau Tao yang rupanya datang bersamaan dengan adanya hubungan dengan China. Agama Islam datang ke Bali dan tidak mendapat respon atau dipeluk oleh masyarakat Bali. Agama ini sudah ada di Bali abad XIV. Sejak saat itu orang-orang Islam berdatangan ke Bali, terkait dengan kepentingan politik masing-masing kerajaan di Bali. (Wijaya, 2005:36). Penganut Agama Islam adalah para pendatang seperti suku Jawa, Bugis, Sasak, dan Madura. Dalam perkembangan berikutnya pemeluk Agama Islam datang ke Bali berkaitan dengan perdagangan dan mencari nafkah di Bali. Di beberapa daerah utamanya penganut Agama Islam yang terkait dengan kerajaan-kerajaan di Bali umumnya menyatu dalam arti kegiatan suka dan duka dengan komunitas Hindu di Bali dengan tetap mempertahankan identitas agama termasuk budaya asal etnis yang bersangkutan. Bersambung ke post berikutnya |
Tantangan Agama Hindu dan Budaya Bali
Tantangan era globalisasi yang dihadapi masyarakat dan kebudayaan Bali seperti dikemukakan oleh Ardika (2005:18) dengan mengutip Appadurai dicirikan oleh perpindahan orang (ethnoscape), pengaruh teknologi (technoscape), pengaruh media informasi (mediascape), aliran uang dari negara kaya ke negara miskin (financescape), dan pengaruh ideologi seperti HAM dan demokrasi (ideoscape) tidak dapat dihindari oleh kebudayaan Bali. Sentuhan budaya global ini menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan atau kehilangan orientasi (disorientasi) dan dislokasi hampir pada setiap aspek kehidupan masyarakat. Konflik muncul di mana-mana, kepatuhan hukum semakin menurun, kesantunan sosial diabaikan. Masyarakat cenderung bersifat sekuler dan komersial. Uang dijadikan sebagai tolok ukur dalam kehidupan. Dilihat dari perspektif Agama Hindu, kondisi zaman dewasa ini telah dinujumkan dalam kitab-kitab Purana yang menyatakan bahwa sejak penobatan prabhu Pariksit cucu Arjuna sebagai maharaja Hastina pada tanggal 18 Februari 3102 SM., umat manusia telah mulai memasuki zaman Kaliyuga (Gambirananda,1984:XIII). Kata Kaliyuga berarti zaman pertengkaran yang ditandai dengan memudarnya kehidupan spiritual, karena dunia dibelenggu oleh kehidupan material. Orientasi manusia hanyalah pada kesenangan dengan memuaskan nafsu indrawi (Kama) dan bila hal ini terus diturutkan, maka nafsu itu ibarat api yang disiram dengan minyak tanah atau bensin, tidak akan padam, melainkan menghancurkan diri manusia. Ciri zaman Kali (Kaliyuga) semakin nyata pada era globalisasi yang ditandai dengan derasnya arus informasi, dimotori oleh perkembangan teknologi dengan muatan filsafat Hedonisme yang hanya berorientasi pada material dan usaha untuk memperoleh kesenangan nafsu berlaka. Dengan tidak mengecilkan arti dampak postif globalisasi, maka dampak negatifnya nampaknya perlu lebih diwaspadai. Globalisasi menghapuskan batas-batas negara atau budaya suatu bangsa. Budaya Barat yang sekuler sangat mudah diserap oleh bangsa-bangsa Timur dan bila hal ini tidak terkendalikan tentu menghancurkan budaya atau peradaban bangsa-bangsa Timur. Di mana-mana nampaknya masyarakat mudah tersulut pada pertengkaran. Kitab Skanda Purana, XVII.1 menyebutkan pusat-pusat pertengkaran yang menghancurkan kehidupan manusia, yaitu pada: kekuasaan (politik), minuman keras, perjudian, pelacuran, dan harta benda/kekayaan (Mani, 1989:373). Berdasarkan uraian di atas, dampak negatif globalisasi terhadap Agama Hindu dan budaya Bali antara lain di bidang moralitas, solidaritas, dan bahkan banalisasi9. Akibat dampak negatif tersebut cenderung bermanifes menjadi potensi konflik seperti dikemukakan oleh Suacana (2005:5) sebagai berikut. 1) Konflik antaretnis khususnya etnis Bali dengan non-Bali. Potensi ini makin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis di antara manusia Bali yang makin membuat tembok pembatas antara �kekitaan� dan �kemerekaan� (we-ness dengan other-ness). Beberapa wacana sosial juga sudah menjadi indikator jelas mengenai hal ini. Kenyataan ini berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali serta meningkatnya inmigrasi dari luar pulau Bali. 2) Konflik antar kelas yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah yang merasa termarginalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya penguasa (investor). Tindakan anarkhi pun mulai menggejala. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pemogokan kaum buruh di berbagai industri pariwisata. 3) Konflik antarkelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus. Kelompok homo-aequalis dengan ideologi egalitarianisme ingin melihat masyarakat Bali yang demokratis, tanpa adanya diskriminasi atas dasar keturunan. Di lain pihak, kelompok homo-hierarchicus dengan segala upaya mempertahankan status quo hirarki tradisionalnya. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1920-an ini secara awam dikenal sebagai konflik kasta10. 4) Konflik antara Hindu tradisional-ritualistik dan Hindu modern-humanistik. Meskipun tidak terlalu menonjol, sudah ada gejala-gejala pertentangan antara penganut Hindu tradisi, yang menekankan pada ritus-ritus besar dengan penekanan Bali, dan Hindu modern yang menekankan pengamalan Hindu dengan konsep �back to Veda� yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai �aliran baru�. Kristalisasi indikator kontemporer masalah ini sangat jelas tampak dengan adanya dualisme Parisada Bali yang berlangsung hingga saat ini, yakni Parisada vesi Campuhan dan Besakih. 5) Konflik antarkabupaten/kota, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah (UU No.22 Tahun 1999), yang memunculkan arogansi kabupaten/kota secara berlebihan. Berbagai potensi dan manifestasi konflik tersebut, makin memberi penyadaran bahwa masyarakat multikultural di Bali ternyata tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi apalagi dalam kondisi masyarakat Bali yang pemilahan, fragmentasi, serta polarisasi sosialnya relatif tinggi. Kondisi diferensiasi sosial demikian serta berbagai ancaman konflik yang menyertainya makin memberi penyadaran bahwa upaya untuk lebih mengaktualisasikan dan mengimplemetasikan nilai-nilai bersama, serta mengembangkan toleransi sudah sangat mendesak dilakukan (Suacana, 2005:6). Sejalan dengan upaya yang ditawarkan oleh I Wayan Gede Suacana di atas, I Wayan Geriya menyatakan: �Pada dasarnya masyarakat Bali memiliki tumpuan dan referensi potensi untuk menghadapi aneka tantangan, baik potensi normatif seperti konsep, nilai, dan filosofis maupun potensi real yang mencakup institusi dan pengalaman bersama dalam menghadapi berbagai gangguan dan ancaman� (20-02-0 6. Gangguan dan ancaman terbukti dari tragedi bom Kuta (12 Oktober 2002) dan tragedi bom Jimbaran (1 Oktober 2005) yang bila tidak ada kearifan masyarakat Bali memungkinkan terjadi konflik yang lebih besar seperti halnya yang terjadi di Ambon maupun Poso. Berkenaan dengan potensi konflik yang dihadapi sebagai dampak negatif dari globalisasi yang menimpa Bali kiranya perlu dilakukan beberapa langkah aksi, antara lain. 1) Menumbuh kembangkan konsep atau nilai kesadaran persaudaraan yang sejati intern umat Hindu, antaragama, dan antaretnis, yakni kesadaran menyamabraya, sebagai wujud solidaritas yang telah tertanam sejak pertumbuhan budaya Bali. Setiap penduduk Bali mesti memiliki kesadaran untuk membangun Bali dan bukan membangun atau hanya mencari keuntungan di Bali. 2) Menumbuh kembangkan kesabaran sebagai wujud pengamalan ajaran agama dengan menempuh musyawarah untuk mufakat. Tindakan anarkhis tidak akan pernah menyelesaikan masalah. 3) Meningkatkan kualitas pendidikan Agama Hindu bagi umat Hindu di Bali yang menekankan pada humanisme, inklusifisme, pluralisme dan dialogis, dengan demikian konflik antarkelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus yang laten dan berlarut-larut dapat direduksi. Dengan kesadaran bahwa semua makhluk (manusia) adalah bersaudara (Vasudhaiva kutumbhakam) dan semua makhluk hendaknya sejahtera (sarvapranihitankarah) maka orang-orang yang benar-benar mengamalkan ajaran Agama Hindu akan menjadi rendah hati, tidak arogan, dan bahkan tidak eksklusif. 4) Memperjuangkan terus otonomi daerah di tingkat provinsi untuk mencegah konflik antarkabupaten/kota. 5) Memperjuangkan peradilan Agama Hindu di Bali sejalan dengan Otonomi Daerah dengan kekhasan budaya Bali untuk mencegah penafsiran yang keliru terhadap ajaran dan hukum Agama Hindu, antara lain yang menyangkut kepanditaan, kepemangkuan, sidhikara, perkawinan dan sebagainya. Selanjutnya dalam usaha untuk tetap ajegnya Agama Hindu dan budaya Bali perlu terus menerus dikembangkan pemahaman dan pengamalan berbagai kearifan lokal yang merupakan warisan leluhur masyarakat Bali, antara lain sebagai berikut. 1) Kearifan untuk mengharagai kepercayaan prasejarah seperti Bhattara Da Tonta di Terunyan, yang kini disebut sebagai Bhatara Pancering Jagat (Dewata Tertinggi masyarakat Terunyan), dalam wujud arca megalitik dan kini ditempatkan dalam bangunan suci meru, yang merupakan bangunan suci menurut Agama Hindu. 2) Kearifan untuk menghargai kepercayaan yang berbeda di antara kepercayaan China (Kong Hu Chu) dengan membangunan satu bangunan suci untuk memuja Ratu Subandar (dari kata Syahbandar) yang di masa silam menangani pelabuhan termasuk pajak berkaitan dengan pelabuhan dan lalulintas barang. Bangunan suci ratu Subandar (yang juga disebut Kong Cho) dapat dijumpai di Pura Agung Besakih, Pura Ulundanu Batur, Pura Dalem Balingkang, di bebera Pura Desa di Kecamatan Kintamani dan lain-lain. Di Goa Gajah ditemukan peninggalan Agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan. Di Pura Silayukti, Mpu Kuturan dipuja sebagai penganut Siva dan Buddha, dan lain-lain. 3) Ajaran Tattvamasi dan Vasudhaiva Kutumbakam, yang memandang bahwa setiap makhluk hakekatnya sama, karena ada atma yang menghidupkan setiap makhluk dan memahami bahwa semua makhluk adalah bersaudara, bagaikan sebuah keluarga. 4) Ajaran Tri Hitakarana yang artinya tiga hal yang menyebabkan terwujudnya kebahagiaan dengan membina hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa) (Parhyangan), antar sesama umat manusia (Pawongan), dan manusia dengan alam sekitar termasuk makhluk rendahan lainnya (Pelemahan). 5) Konsepsi Desa, Kala, dan PatraKonsepsi ruang, waktu manusia yang berintikan penyesuaian atau keselarasan serta dapat menerima perbedaan dan persatuan sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika. Konsepsi ini memberikan landasan yang luwes dalam komunikasi ke dalam maupun ke luar, sepanjang tidak menyimpang dari essensinya. 6) Konsepsi Karmaphala. Konsepsi berlandaskan hukum sebab akibat karena perbuatan yang baik akan selalu menghasilkan pahala yang baik dan demikian sebaliknya. Konsepsi ini merupakan landasan bagi pengendalian diri dan dasar penting bagi pembinaan moral dalam berbagai segi kehidupan. 7) Konsepsi Taksu dan Jengah. Taksu dan Jengah merupakan dua konsep dalam kebudayaan Bali yang perlu dihayati dan dikembangkan, karena sangat relevan untuk menjaga ketahanan dan keajegan budaya Bali, yakni sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu yang dapat memunculkan talenta dan rasa untuk malu bila sesuatunya itu gagal dilakukan. 8) Konsepsi Salunglung Sabhayantaka, Paras Parosarpanaya, atau Beriuksaguluk. Kalimat tersebut mengandung makna solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik dan buruk ditanggung bersama. Bersama-sama dalam kegiatan baik suka maupun kedukaan. 9) Konsepsi Wirang dan Tindih. Konsepsi untuk membela teman seperjuangan, membela nama baik kekerabatan, nama baik desa dan sejenisnya. 10) Konsepsi Satyam-Sivam-Sundaram. Konsepsi berkaitan dengan kebenaran-keharmonisan-keindahan yang merupakan landasan estetika kesenian Bali. 11) Konsepsi Asih-Punya-Bhakti. Makna yang dikandung dari konsepsi ini adalah cinta kasih, jasa, dan penghormatan yakni hubungan yang harmonis antara Manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, para Dewa dan leluhur, juga hubungan yang harmonis antara yang lebih muda, sebaya dan dengan yang lebih tua. 12) Konsepsi Desa Amawacara Nagara Amawa Tata. Makna konsepsi ini adalah untuk menghargai perbedaan tradisi budaya masing-masing, demikian pula dalam dimensi waktu yang berbeda. 13) Konsepsi Tri Samaya (Atita - Wartamana - Anagata). Konsepsi dalam konteks dimensi waktu yakni: yang lalu, yang terjadi saat ini, dan yang terjadi di masa yang akan datang, dan lain-lain. Simpulan Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa sinergi Agama dan budaya Bali mampu menjadikan Bali tegar dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Berbagai konsep, nilai, filosofi, potensi real yang mencakup institusi dan pengalaman bersama terbukti mampu dijadikan pegangan dalam menghadapi berbabagai tantangan globalisasi. Mengakhiri tulisan ini kata-kata Mahatma Gandhi yang dikutip pada manggala tulisan ini patut untuk dijedikan renungan. Catatan 1 Tentang sejarah perkembangan Agama Hindu di Bali dapat dilihat pada Disertasi penulis �Persepsi Umat Hindu di Bali tentang Svarga, Naraka, dan Moksa dalam Svargarohanaparva, Perspektif Kajian Budaya� yang akan diterbitkan oleh Paramita, Surabaya, pada bulan Agustus 2006, demikian pula dapat dilihat pada I G. P. Phalgunadi, �Bali Embraces Hinduism� dalam �Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Kusumanjali untuk Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudharta, MA, Editor Darma Putra & Windhu Sancaya, 2005, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan. 2 Meru dilihat dari fungsinya dibedakan menjadi (1) Meru sebagai sarana untuk memuja manifestasi Tuhan Yang Maha Esa, dan (2) Meru sebagai salah satu sarana untuk memuja roh suci leluhur, yakni roh suci yang telah diupacarakan melalui upacara �Nuntun Dewa Hyang�, pada zaman Majapahit disebut upacara Sraddha yakni men-dharma-kan roh suci leluhur pada tempat suci yang ditentukan untuk itu. Upacara Sraddha ini hingga kini juga dilaksanakan di India, sebagai bentuk penghormatan dan pemujaan kepada leluhur. 3 Tentang keberadaan kesenian, khususnya seni pertunjukkan lihat Claire Holt, 2000. Melacak jejak Perkembangan Seni di Indonesia, Terjemahan dari Art in Indonesia: Continuities and Change. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia. Juga dalam Sartono Kartodirdjo, Maewati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto, 1976. Sejarah Nasional Indonesia II. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hal.84-85. 4 Lihat karya C.Hooykaas and T. Goudriaan. 1971. Stuti and Stava (Bauddha, Saiva, and Vaisnava) of Balinese Brahman Priests, C. Hooykaas. 1964. Agama Tirtha, Five Studies in Hindu-Balinese Religion. 1966. Surya Sevana. The Way to God of a Balinese Siva Priest, dan lain-lain. 5 Lihat Dubois, Abbe J.A.1981. Hindu Manners, Customs and Ceremonies. Delhi: Oxford University Press, p. 569. Sivananda, Swami. 1991. Intisari Ajaran Hindu (Terjemahan All About Hinduism), Surabaya: Paramita, hal.8, dan I G. P. Phalgunadi, �Bali Embraces Hinduism� dalam �Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi, Kusumanjali untuk Prof. Dr. Tjokorda Rai Sudharta, MA, Editor Darma Putra & Windhu Sancaya, 2005, Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Pustaka Larasan. 6 Terdapat beberapa jenis makanan yang di India dan Bali menampakkan persamaan, misalnya satu atau laddhu di Bali dikenal dengan sebutan satuh. Demikian pula sesaji yang disebut puja di Bali disebut daksina. Penggunaan hiasan bunga pada kepala wanita di India selatan memiliki kesamaan dengan hiasan kepala pada wanita Bali dan sebagainya. 7 Tentang kesenian Bali, Ida Bagus Mantra menyatakan: �Landasan-landasan yang mendalam mendasari kebudayaan Bali: 1) Agama Hindu adalah sumber inspirasi dari seni budaya Bali. Seni sakral sebagai akibat dari ini sangat mendalam dan meresap dalam jiwa umatnya; 2) seni tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya, ia adalah satu. Oleh karena itu nilai estetik, keindahan adalah sangat kuat dalam masyarakat Bali. Sangat tinggi kesadaran seninya. Antara seniman dan masyarakat penontonnya terdapat komunikasi yang hidup; 3) seni mempunyai fungsi dalam masyarakat dan mempunyai kedudukan sosial yang dihormati. Sebagai wayang, ketekok jago dan lain-lainnya, ia dipentaskan/dipertunjukkan pada waktu upacara-upacara tertentu; 4) seni dilihat sebagain unsur yang dapat menumbuhkan rasa kemuliaan dalam hidup. 8 Lihat Goris, R.1954. Prasasti Bali, I-II. Bandung: NV Masa Baru, juga tulisan I Wayan Gede Suacana.2006. Budaya Demokrasi Dalam Kehidupan Masyarakat Desa di Bali, tulisan dipersiapkan untuk diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2006. 9 Tentang banalisasi lihat tulisan kami (2005) Ajeg Bali: Perspektif Pengamalan Agama Hindu, dalam Dialog Ajeg Bali, Kata Pengantar Anak Agung Gde Putra Agung: Surabaya: paramita. 10 Kesalahpahaman tentang Warna diartikan sebagai Kasta dapat dilihat pada tulisan Nyoman Singgin Wikarman (1998:60) yang menyatakan bahwa sejak pemerintahan Dalem Waturenggong terjadi legimitasi yang hanya boleh menjadi pandita dan mempimpin upacara umat hanyalah keturunan Purohita Raja Dalem Waturenggong yakni Danghyang Nirartha (Danghyang Dwijendra) dan keturunan Danghyang Astapaka. Selanjutnya ditetapkan pula Tri Sadhaka yang boleh memimpin upacara-upacara besar tadi, yakni Pandita Siva (keturunan Danghyang Nirartha), Pandita Buddha (keturunan Danghyang Astapaka) dan Rsi Bhujangga Vaisnava (keturunan Mpu Mustika). Pada mulanya masyarakat Bali menganut sistem �varna�, lalu kemudian disusun berdasarkan �Vangsa�, dan keluarga beliau (Danghyang Nirartha termasuk keturunan Danghyang Astapaka) menduduki posisi sebagai Brahmana Vangsa. Ksatriya Vangsa diisi oleh para keluarga/keturunan Dalem (Raja). Para Arya didudukkan sebagai Vaisya (Waisya), dan Sudra adalah di luar warga tadi, dengan tidak melihat asal-usul mereka. Upaya penjernihan tentang Kasta di Bali, dapat dilihat dalam Ketut Wiana dan Raka Santeri, 1993. Kasta dalam Hindu: Kesalahan Berabad-Abad. Denpasar: Yayasan Dharma Narada. Sekian dan Terima Kasih Mudah-Mudahan Berguna Sumber: Parisada Hindu Dharma Indonesia |
| All times are GMT +7. The time now is 10:27 PM. |