
12th May 2011
|
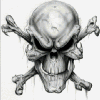 |
Ceriwis Geek
|
|
Join Date: Nov 2010
Location: PIC#01
Posts: 19,459
Rep Power: 0
|
|
 Delapan Pasal RUU Terorisme Ini Jadi Sorotan Aktivis
Delapan Pasal RUU Terorisme Ini Jadi Sorotan Aktivis

TEMPO/Aditia Noviansyah
Quote:
TEMPO Interaktif, Jakarta - The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) menilai draf revisi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang disiapkan pemerintah memiliki beberapa masalah yang justru memperkeruh dan memperkuat ketidakseimbangan antara keamanan dan kebebasan sipil. Berikut delapan poin yang dikritik dan menjadi sorotan LSM yang fokus mengawasi dan menyelidiki pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini.
1. Ketentuan tindak pidana yang obscure.
Terdapat dalam Pasal 9A RUU perubahan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperdagangkan bahan-bahan potensial sebagai bahan peledak, atau membahayakan jiwa manusia dan/atau lingkungan dapat dianggap sebagai teroris dan dijerat dengan RUU ini. Frase �bahan-bahan potensial� dalam RUU ini tidak dijelaskan, sehingga mudah ditafsirkan dengan leluasa oleh kekuasaan.
Bahkan, dalam Pasal 13B poin B seseorang dapat dipidana dengan tindak pidana terorisme hanya karena meminta atau meminjam uang dan/atau barang dari organisasi atau kelompok yang secara nyata bertujuan melakukan tindak pidana terorisme. Pasal ini juga bersifat karet dan multitafsir
2. Definisi �Tindak Pidana Terorisme� yang masih terlalu luas.
Definisi �tindak pidana terorisme� masih sama dengan ketentuan yang diatur dalam UU yang lama, sehingga dapat ditafsirkan dengan leluasa oleh kekuasaan, hal ini ditambah lagi dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 13A RUU perubahan.
3. Laporan Intelijen dijadikan sebagai bukti permulaan.
Semakin menegaskan bahwa laporan intelijen bisa berfungsi sebagai bukti pokok (primary evidence). Sebagaimana terdapat dalam Pasal 26 RUU perubahan. Laporan intelijen sering tidak memiliki dan memerlukan fakta hukum yang jelas untuk merumuskan sebuah perbuatan sebagai dasar adanya indikasi tindak pidana. Sedangkan di pengadilan, untuk merumuskan sebuah �perbuatan melawan hukum� harus memiliki fakta hukum yang konkret dan jelas.
4. Masa penangkapan yang terlalu lama.
Pasal 28 Rancangan perubahan UU Terorisme menambah kewenangan kepada kepolisian untuk dapat menangkap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme paling lama 30 hari. Perpanjangan masa penangkapan ini terlalu berlebihan mengingat di KUHP masa penangkapan hanya satu hari. Sedangkan di UU 15 Tahun 2003 masa penangkapan tujuh hari.
Selama ini, dengan masa penangkapan tujuh hari saja aparat kepolisian sudah berhasil menangkap pelaku terorisme dan membongkar jaringan terorisme. Dengan demikian masa penangkapan tidak perlu lagi diperpanjang karena perpanjangan masa penangkapan tidak memiliki dasar alasan yang kuat dan terlalu berlebihan.
Perpanjangan masa penangkapan secara sepihak oleh penyidik tanpa mekanisme kontrol dalam masa perpanjangan dan tidak diaturnya pengaturan tentang hak rehabilitasi dan kompensasi warga akan berpotensi melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini juga tidak sejalan dengan prinsip sistem peradilan pidana harus menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Masa penahanan yang terlalu lama.
Masa penahanan untuk proses penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam RUU ini jika digabungkan berjumlah 420 hari, atau sekitar 14 bulan. Di mana sebelumnya dalam UU No. 15 Tahun 2003 masa penahanan ditentukan selama enam bulan tanpa ada perpanjangan waktu. Hal ini jelas sangat tidak efektif dan bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Bila dibandingkan dengan KUHAP masa penahanan sejak dari penyidikan dan penuntutan hanya berjumlah 120 hari, atau empat bulan.
6. Kewenangan BNPT yang luas.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebelumnya telah diatur berdasarkan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010. Dalam RUU ini, BNPT diberikan kewenangan yang terlalu luas, seperti kewenangan penindakan, yang sebenarnya tidak perlu, yang diberikan kepada BNPT. Seharusnya lembaga ini lebih bersifat koordinatif dan hanya merumuskan kebjiakan penanggulangan terorisme.
7. Memuat ketentuan tentang hukuman mati.
UU No. 15 Tahun 2003 masih memuat ketentuan tentang pemberlakuan hukuman mati. Hal ini tentunya selain bertentangan dengan hak asasi manusia juga dapat menyuburkan aksi terorisme yang bersifat ideologis. Hukuman mati bahkan menjadi tujuan (syahid) bagi sebagian teroris yang melakukan aksinya dengan latar belakang ideologis.
8. Pengaturan tentang pasal mengenai penebaran kebencian tidak rigid.
Dalam RUU ini pengaturan mengenai penebaran kebencian hanya diatur dalam satu pasal, yakni Pasal 13B poin E. Hal ini tentunya akan menimbulkan multitafsir yang sangat luas, sehingga dapat menimbulkan persoalan terhadap HAM.
Seharusnya pengaturan pasal mengenai penebaran kebencian diatur dalam rambu-rambu yang lebih jelas, sehingga tidak membuka ruang terjadinya abuse of power. Pengaturan tentang hal ini lebih baik diatur secara lebih rigid dan jelas melalui revisi KUHP ataupun undang-undang tersendiri.
MUNAWWAROH
|

|