Kebrutalan Otonomi Daerah yang Mengesampingkan Aspek Lingkungan Hidup
Seiring dengan pelaksanaan penerapan desentralisasi dalam Otonomi daerah, kita dihadapkan dengan permasalahan lingkungan hidup yang sangat krusial, pencemaran berbagai media lingkungan hidup (tanah, sungai, laut dan udara) terus berlangsung. Bencana alam sebagai buah dari salah kelola lingkungan hidup sumberdaya alam intensitas, kwantitas, dan karakternya semakin tinggi dan brutal. Peningkatan temperature (pemanasan global) dan perubahan iklim semakin dahsyat dengan dampaknya yang semakin ekstrim.
Penyempitan dan penyusutan sumberdaya alam dalam era otonomi ini tidak terlepas dari proses pengambilan keputusan, secara politis SDA dijadikan pelayan bagi kepentingan yang berorentasi pada kekuatan politik dalam penguasaan dan pengusaan asset didaerah. Sementara masyarakat yang sejatinya memiliki hak Otonomi tersingkir dan diasingkan dari proses pengambilan keputusan untuk terlibat dalam proses pengelolaan sumber-sumber kehidupannya, sehingga pola penguasaan ini berujung pada konflik kepentingan diantara beragam pihak dengan masyarakat local.
Paradigma pembangunan yang telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, secara substantif tidak ada perbedaan yang berarti, hanya merupakan jarg�n pembangunan yang mendukung penuh paradigma dan agenda neoliberal, serta korporatokrasi dalam memangsa sumber-sumber kehidupan masyarakat kita. Ini merupakan landasan petaka dan tragedi sejarah yang kejam, sehingga nantinya
masyarakat akan tereleminasi dari harapan dan masa depan yang dicita-citakan.
Dapat kita lihat bagaimana kuat dan perkasanya Pemerintah dalam mendorong lahir Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang memberikan ruang bagi investasi (modal) untuk menghancurkan benteng terakhir ikhtiar perlindungan sumber daya hutan. Sementara pendapatan negara hanya didapat dari royalti, pajak, dan iuran perusahaan yang tidak seberapa nilainya bila dibandingkan dengan yang dibawa ke luar Indonesia. Jadi pengelolaan yang salah selama ini dianggap sebagai
prestasi monumental dalam konglomerasi sumber daya alam dan hutan yang identik dengan praktek kapitalisme, dan memarginalkan masyarakat yang
survive dari sumber daya hutan.
Posisi masyarakat mulai dari masyarakat umum, ORNOP, akademisi, mahasiswa, profesional, hingga media sebagai subyek dari pelaksanaan Program Restorasi Ekologis menuntut pemerintah untuk membuka akses seluas-luasnya bagi publik untuk berperan aktif. Peran ini didasarkan pada hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan atas informasi (rights to information), hak atas lingkungan (rights to environment), hak atas pembangunan (rights to development) dan hak untuk berpartisipasi (rights to participation). Disini media memainkan peran yang penting dalam distribusi informasi dan meningkatkan kesadaran publik.
__________________
ﷲ ☯ ✡ ☨ ✞ ✝ ☮ ☥ ☦ ☧ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ✌
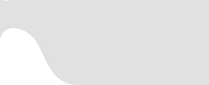
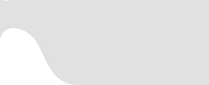


 orng tuh pada arogan ,tp mereka ga mkir pdhal yg dirusak tuh mempengaruhi mreka jg
orng tuh pada arogan ,tp mereka ga mkir pdhal yg dirusak tuh mempengaruhi mreka jg

 ....
....
